OPINI: Keadilan Hukum bagi Penyintas Rasialisme
OLEH : ASKAR NUR
(Mahasiswa Jurusan Bahasa & Sastra Inggris Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin Makassar).
“Dasar! Kalian semua sampah”. Dengan perasaan terkejut, saya mencoba kembali membaca berita di linimasa tersebut untuk sekedar memastikan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat saya membaca postingan di beranda facebook dengan seksama, saya menemukan bahwa yang dimaksud ‘sampah’ itu adalah sekelompok orang yang bekerja di sebuah institusi pendidikan dan tempat yang mereka tempati bekerja ternyata tidak jauh dari lingkungan saya. Sebuah panggilan yang keluar dari seseorang yang bisa dibilang salah satu atasan kepada bawahannya.
Singkat cerita, pasca panggilan yang ganjil itu mendarat di telinga mereka, rapat pun mereka gelar. Beberapa di antaranya merasa emosi, tentunya perasaan itu adalah sebuah kewajaran. Kiranya kita posisikan diri, kita berada di kondisi itu tentu perasaan yang sangat tidak mengenakkan akan kita rasakan pula. “Meskipun kita ini semua miskin dan bekerja sebagai bawahan di kampung sendiri, tentu kami tidak terima dengan perkataan seperti itu”, tutur salah seorang dengan nada yang sedikit tinggi.
“Kami masyarakat yang masih memegang teguh nilai budaya. Konsep Siri na Pacce masih kita pegang teguh, kiranya panggilan ‘sampah’ pada kami adalah sebuah pantangan begitupula dengan masyarakat lainnya yang tentu menjadikan perkataan-perkataan seperti itu adalah sesuatu yang pantang dikeluarkan”, lanjutnya dengan penuh kegetiran.
Setelah dipastikan semuanya, keesokan harinya dikabarkan bahwa sang pejabat tersebut meminta maaf kepada para bawahannya dan mengatakan bahwa ujaran ‘sampah’ yang pernah ia utarakan hanyalah bercanda semata. Antara kata maaf dan khilaf adalah dua kata yang tidak asing lagi terdengar di telinga setelah perlakuan tidak mengenakkan menimpa seseorang. Lantas apakah ketika kata maaf ataupun khilaf atas perlakuan telah diutarakan mampu menyembuhkan luka dan yang terpenting perlakuan tidak mengenakkan itu tidak terulang lagi? Semoga sirkulasi pemaafan dan khilaf tidak hanya menjadi alat peredam kesalahan dan suatu saat akan terulang lagi.
Cerita panggilan ‘sampah’ berakhir dengan pemaafan. Kata maaf seharusnya menjadi komitmen untuk tidak mengulang kembali perlakuan yang sama karena sehormat-hormatnya manusia adalah ia mampu adil terhadap perkataan apalagi perlakuan.
Di lain waktu dan cerita, tepatnya seminggu setelah peristiwa panggilan ‘sampah’ itu. Kembali saya menemukan informasi di beberapa beranda akun sosial media. Sebuah informasi tentang keganjilan panggilan bagi sekelompok orang, panggilan yang berbeda seperti peristiwa sebelumnya. Setelah panggilan ‘sampah’ dialamatkan ke sekelompok orang yang bekerja sebagai bawahan di sebuah institusi pendidikan, kini panggilan ‘monyet’ yang diarahkan tepat pada pribadi sekelompok orang yang hidup di bagian timur Indonesia yang tengah menuntut ilmu di pulau Jawa. Mereka adalah mahasiswa yang berasal dari Papua.
Beberapa media mengabarkan kondisi persekusi dan rasialisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. Awal mula kejadian yang dikutip dari Makassar Terkini.id, pada Jumat, 16 Agustus 2019, sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) memadati asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan mereka karena ada kabar bahwa mahasiswa Papua di asrama tersebut diduga mematahkan tiang bendera Merah Putih dan membuangnya ke selokan. Namun saat massa datang, bendera Merah Putih terlihat terpasang di halaman asrama.
Dikutip dari Kompas, Jubir Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya menerangkan kronologis kejadian. Saat asrama dipadati ormas, aparat keamanan diduga merusak pagar asrama dan mengeluarkan kata-kata rasisme. Kemudian tentara masuk depan asrama disusul Satpol PP lalu merusak semua pagar dan melayangkan kata-kata rasis (monyet). Selanjutnya disusul oleh sekelompok ormas yang turut bersikap reaksioner dengan melemparkan batu ke dalam asrama.
Rasialisme dalam KBBI adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa; perlakuan yang berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda; paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Perlakuan yang berat sebelah terhadap suatu suku bangsa, hal demikian dapat diliat dari ujaran-ujaran yang tidak sepantasnya seperti menamai sekelompok orang sebagai ‘sampah’, ‘monyet’ dan ujaran-ujaran lainnya. Mungkin itu terbilang hal dan kesalahan kecil tapi justru dari hal-hal kecil itu mampu berkembang menjadi besar hingga memecah belah.
Apatah lagi ujaran itu justru lahir dari mulut sekelompok elite atau apparatus pemerintah, yang sedari awal mengkampanyekan ketertiban dan keamanan negara, dan ideologi negara beserta konsep Bhinneka Tunggal Ika telah terinternalisasi dalam dirinya dan sudah menjadi bahasa sehari-hari. Seharusnya kita mampu berlaku adil sejak dari dalam pikiran, perkataan hingga menerapkan pikiran dan perkataan dalam perbuatan untuk kepentingan sesama. Sebaik-baik dan sehormat-hormatnya manusia adalah ia mampu bermanfaat bagi yang lain, seburuk-buruknya manusia adalah ia yang dimanfaatkan oleh yang lain.
Papua adalah bagian dari Bumi Pertiwi, Papua adalah Indonesia. Desas-desus mengenai keinginan Papua untuk lepas dari Indonesia merupakan ihwal yang harus diperhatikan dengan serius. Salah satu bentu kebijaksanaan dan amanahnya seorang pemimpin sebuah negara adalah mendengarkan cerita para warga negaranya. Desas-desus itu kiranya tidak disalahartikan apalagi menjurus pada tudingan bahwa keinginan Papua untuk lepas dari Indonesia adalah sebagai penghancur keutuhan dan pengganggu ketertiban negara sehingga harus mengambil langkah ‘tegas’. Papua butuh didengarkan secara langsung karena pada dasarnya munculnya keinginan untuk berpisah terhadap suatu perkara tentu memiliki sebuah alasan. Dan kiranya alasan tersebut harus diketahui secara jelas.
Memaksakan kehendak terhadap sebuah perkara adalah tirani. Sikap tirani tentu tidak dianjurkan baik dari segi agama maupun segi kecintaan (nasionalisme). Cinta tak bisa dipaksakan, kiranya kita ketahui bersama. Misalnya cinta terhadap tanah kelahiran, kita mencintai karena kita mempunyai pengetahuan tentangnya dan karena kita memperlakukan-diperlakukan dengan baik.
Menamai sekelompok orang sebagai ‘sampah’ dan berakhir dengan kata ‘maaf’ merupakan tindakan yang masih kurang elegan namun bukan berarti maaf tidak dibutuhkan ataupun tidak penting melainkan kata ‘maaf’ saja tidak cukup. Setidaknya ada dua jenis pemaafan, meminta maaf untuk melupakan peristiwa (namun tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi) dan meminta maaf sebagai strategi untuk menghegemoni. Sebuah keharusan kata ‘maaf’ harus diikuti dengan penegakan dan pendirian hukum yang berkeadilan.
Sastrawan ternama Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, pernah terlibat peristiwa maaf-memaafkan dengan Gus Dur (sebagai Presiden RI saat itu) yang dikisahkan oleh Gunawan Muhammad melalui surat terbuka bagi Pram yang dimuat di Majalah Tempo 3-9 April 2000. Dalam surat balasannya terhadap pernyataan GM yang sebelumnya membahas Pram yang tidak mau memaafkan Gusdur atas peristiwa yang pernah menimpanya sebagai tapol melalui gambaran kisah Nelson Mandela yang memaafkan ras kulit putih yang pernah memerangi bangsanya, Pram mengutarakan bahwa “Minta maaf saja tidak cukup. Dirikan dan tegakkan hukum. Semuanya mesti lewat hukum. Tidak pernah ada pengadilan terhadap saya sebelum dijebloskan ke Pulau Buru. Semua menganggap saya sebagai barang mainan. Betapa sakitnya ketika pada 1965 saya dikeroyok habis-habisan, sementara pemerintah yang berkewajiban melindungi justru menangkap saya”.
“Gunawan mungkin mengira saya pendendam”, ujar Pram. “Tidak, saya justru sangat kasihan dengan penguasa yang sangat rendah budayanya, termasuk merampas semua yang dimiliki bangsanya sendiri”.
Begitupun yang seharusnya terjadi terhadap mahasiswa Papua yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Hukum harus tegak dengan keadilannya, menggali secara mendalam terkait tudingan tiang bendera Merah Putih yang dipatahkan dan diceburkan ke selokan hingga menindaklanjuti para pelaku rasialisme. Memecahkan teka-teki dan mengungkap kenyataan dengan prinsip keterbukaan adalah keharusan bagi para penegak hukum agar ketertiban dan ketentraman tetap terjaga di tubuh republik tercinta. Peristiwa ini kiranya sangat disayangkan jika tidak segera dituntaskan apa lagi dibiarkan berlalu begitu saja, peristiwa ini tergolong ‘sensitif’ dan dapat memancing konflik yang berkepanjangan.
Dirikan dan tegakkan hukum yang berprinsip nilai keadilan dan kemanusiaan. Indonesia adalah cinta. Mencintai Indonesia dengan memahami kilas-balik sejarah tentangnya adalah cinta yang diideologis dan hidup. Semoga para penegak hukum pun tidak ‘rasialisme’ dalam proses penegakannya, semoga saja dan itu merupakan harapan kita bersama. (*)
(Penulis merupakan Presiden Mahasiswa DEMA UIN Alauddin Makassar 2018 dan Duta Literasi UIN Alauddin Makassar 2019)




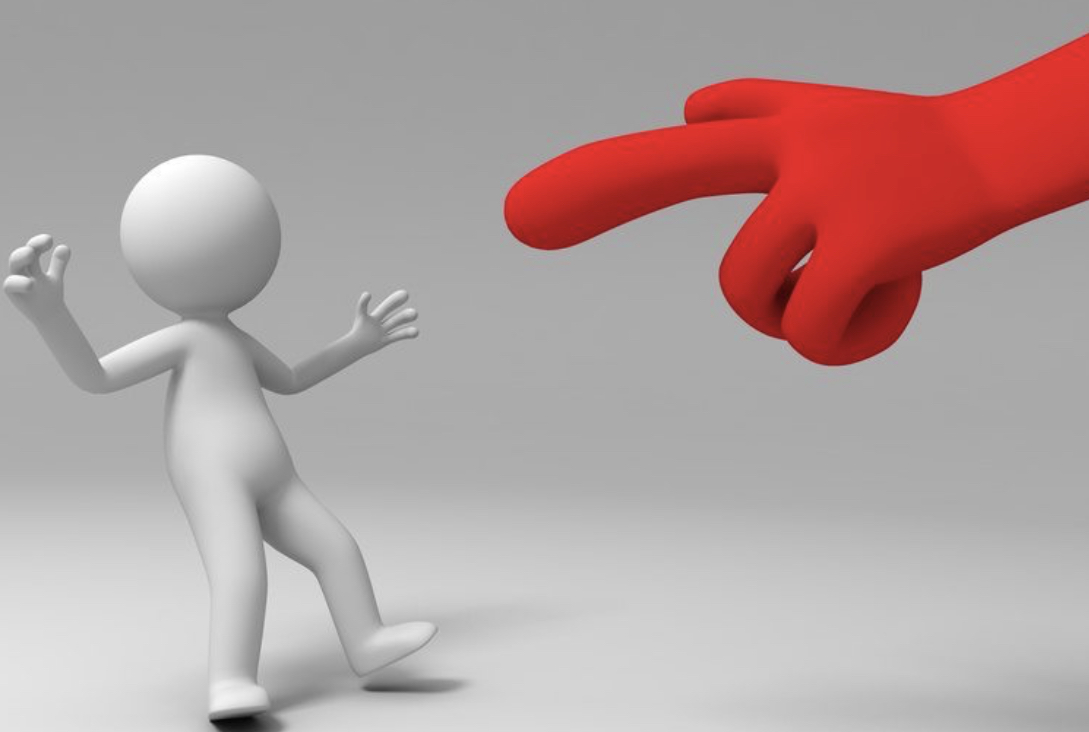

Tinggalkan Balasan